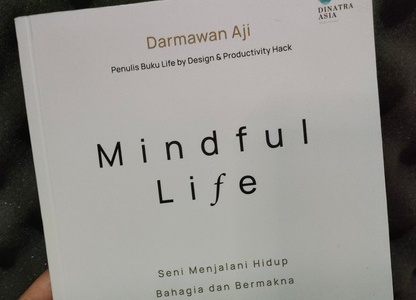A
ku menatap jam digital di pergelangan tanganku. Detiknya lebih cepat berubah dari biasanya. Commuter line yg kutunggu belum menunjukan tanda-tanda akan melintas, sedangkan ratusan orang sudah berjejer siap untuk memenuhi tiap gerbongnya. Ini bukan kali pertamanya aku turut berebut masuk ke dalam gerbong, kekuatan ibu yg rindu anaknya mampu mendorong paksa siapapun yg jauh lebih besar dari tubuhnya agar cepat sampai ke rumah. Namun kali ini aku merasa jengah dengan kondisi ini, ditambah bunyi telpon siang tadi yang mengabarkan anak keduaku sudah 6 kali bolak-balik ke toilet karena diare, rasanya seperti ada ratusan tali yg kusut di kepalaku, tak keruan.
Pukul 16.42 WIB commuter line jurusan Bogor tiba, aku memaksa masuk meski kondisinya sudah tak manusiawi lagi. Gerbong yg aku naiki kapasitasnya sudah jauh melebihi dari kapasitas normal, sesak, bau, rebutan oksigen, dan tentu panas. Rupanya tak hanya aku yg ingin cepat pulang, ada banyak ibu-ibu dengan wajah lelahnya juga sudah tak sabar pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, aura panas masih menjalar di seluruh tubuhku. Tak ada istilah, mau istirahat dulu, aku langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan anak keduaku dalam kondisi tak berdaya dengan muka pucat dan bibir kering. “Unda…” panggilnya tanpa suara, hanya gerakan bibir yg membuka sebentar lalu terkatup.
“Bunda disini nak, apa yg sakit ?” kupeluk dia erat. Bau pup tercium, celananya basah, dan di depan kami ada ember tempat celana kotor berisi pup yg menumpuk. “Ganti celana dulu yuk.” Ajak saya halus, “kita ke dokter ya.”
Sayang, aku terlambat pulang ya, ada meeting dengan klien.
Tiba-tiba sebuah pesan masuk, suamiku mengabari kalau dirinya hari ini lagi-lagi telat pulang. Argh, aku langsung memesan taksi online untuk segera membawa kami ke rumah sakit sore itu juga. Jadu anakku sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi.
“Mbak, aku langsung ke rumah sakit ya. Tolong jaga Jati, kalo aku nggak pulang, tidur aja di kamar tengah sama Jati.” Pesanku ke mba ART yg baru 1 bulan bekerja di rumah.
“Kakak, gimana bunda ?” Jatu, si sulung yg umurnya belum genap 7 tahun menatapku bingung. “Kakak, ikut bunda.” Pintaku tanpa babibu, dan dia langsung dengan sigap mengambil jaket serta tas yg sudah aku persiapkan untuk menemani kami ke rumah sakit.
***
Benar, Jadu anak ku harus menjalani rawat inap karena sudah dehidrasi. Ini salahku karena lupa mengabari si mbak ART untuk sering-sering memberinya minum siang tadi. Aku hanya memintanya memberi makan, tapi rupanya tak berhasil karena Jadu tak nafsu makan. Suamiku sudah membawa si sulung pulang dan menyiapkan barang-barang yg Jadu butuhkan di rumah sakit. Aku tak banyak bicara padanya saat bertemu tadi, hanya memberikan instruksi A,B dan C. Jujur saat itu aku kecewa padanya, kalau saja ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami aku tak perlu bekerja keluar rumah sekedar untuk membantunya membayar cicilan ini dan itu, aku mungkin akan di rumah mendampingi anak-anakku tumbuh sesuai dengan standar ku bukan standar asisten rumah tangga.
Drama ART di keluarga kami sudah mulai masuk ke babak yg ditakutkan ibu-ibu bekerja di seluruh dunia. Bolak-balik ganti sudah tak bisa dielakan di beberapa bulan terakhir ini. Keluar karena hamil, lalu mencari yg pas, keluar lagi karena nggak betah, nyari ke yayasan, ditipu, lalu ke penyalur dan aku merasakan betul bahwa yg sedang aku cari sejatinya bukan baby sitter untuk mengasuh anak-anakku, bukan. Aku sedang mencari diriku sendiriku. Ya, karena Allah SWT telah percaya menitipkannya padaku lalu aku mencari penggantiku untuk menitipkan mereka. Wajar, kalo kemudian Allah menyentil ku hari ini.
Aku menangis tergugu menyaksikan anakku yang histeris karena kesakitan ditusuk jarum beberapa kali di lengannya. Andai bisa dipindahkan rasa sakitnya padaku, tentu aku mau. “Undaa… sakiiiiiiit” Ia berteriak dalam lemah, dan aku hampir emosi menegur perawat yang sedari tadi tak mampu memasukan jarum infus ke tangan kecil Jadu.
“Pembuluh vena anak ibu tertutup kulit kering yg mengeras karena terlalu lama dehidrasi, kami butuh waktu ya bu untuk bisa memasukan jarum infus ini. Jadi ibu lebih baik tunggu di luar.” Kata perawat tadi setengah mengusirku. Aku diam, rasanya ingin sekali menumpahkan sumpah serapah padanya. Sampah di kepalaku siap keluar kalau saja tak ingat bahwa aku dan Jadu membutuhkannya saat ini.
Jam sudah menunjukan angka 10, kami baru mendapatkan kamar untuk perawatan Jadu selama di rumah sakit ini. Jadu juga sudah mulai terlelap dengan pantat basah karena pupnya belum bisa dihentikan. Sebelum aku membersihkan sisa pupnya, handphone ku bunyi. Aku melihat panggilan dari nomor kontak yang dulu aku namai “cintaku”. Ya, saking cintanya nomor kontak di hp saja sampai selebay itu. Aku mengangkatnya ogah-ogahan. “Termos kecil dimana ? si mba nggak tau tempatnya dimana.” Tanyanya setelah mengucap salam.
“Ya, dan kamu bahkan gak tau apapun.” Aku menelan kalimat yang hampir naik ke tenggorokan. Beberapa pertanyaan lain meluncur, dan aku semakin gemas dibuatnya.
“Jati gimana ?” Tanyaku.
“Kayaknya tidur.” Jawabnya cuek.
Aku menahan nafas berat, Allah… kenapa aku bisa jatuh cinta pada orang seperti ini ? hilang sudah kekaguman selama ini tentang sosok suamiku yg rupawan, baik dan sabar. Dalam ingatanku suamiku saat ini adalah sumber masalah yg terjadi dalam hidupku. Rupanya setan menguasai tubuhku sehingga aku mulai menyimpan kemarahan yg teramat dalam padanya.
***
Ini malam kedua aku dan Jadu di rumah sakit. Dari kemarin aku memilih diam didepan suamiku. Malam ini ia memutuskan untuk tidur dirumah menemani dua anakku yang juga butuh sentuhan ayah ibunya. Aku diam saja tak merespon saat ia menyampaikan maksudnya. Dan seperti tau tak butuh dengan persetujuanku ia pulang setelah mencium kening Jadu dan aku terlebih dahulu. Aku tak bisa menghindar, meski ingin. Tapi jujur sentuhannya di tubuhku meredam rasa marah yg meletup-letup. Kami lupa satu hal, bahwa tangki cinta aku dan suamiku hampir kosong karena lama tak bersentuhan. Diam tentu bukan solusi, tapi gengsi merajai diri.
“Say, sorry ya tapi ini harus selesai malam ini juga. Laporan kinerja kita pekan ini ditunggu Pak deputi jam 08.00 besok.” Deg! Aku membaca pesan dari rekan kantorku dengan perasaan kesal, lalu menatap anakku yg baru saja bisa tidur setelah aku bacakan belasan buku yg dibawa ayahnya kemarin. Masih bisa aku selesaikan malam ini, tapi aku harus menghubungi orang rumah untuk segera mengirimkan laptopku saat ini juga.
“Maaf ya sayang, kamu harus tetap bekerja meski dalam kondisi seperti ini.” Aku menerima tas laptop ku beserta surat yg dititipkan suamiku ke ojol dengan mata basah. Ada yg mengalir dingin dihati. Kini aku merutuki diriku yang seharusnya tak kekanakan menghadapi kondisi saat ini yang sama beratnya antara aku dan suamiku. Aku yang terlalu banyak menuntut, merasa sudah berkorban paling banyak dan melupakan bahwa ia juga bukan sedang diam. Ia sedang mengusahakan yang terbaik, dan aku hanya perlu bersabar sembari terus melangitkan do’a.
***
Alhamdulillah pagi ini Jadu bisa pulang, aku menatap punggung suamiku yg sedang membereskan administrasi. Disampingku Jadu sudah bisa tersenyum. Aku menggenggam tangannya riang, sudah terbayang kasur rumah yang nyaman dan nikmatnya mengASIhi si bungsu langsung dari gentongnya. Dari kemarin aku pumping sekenanya, dan bengkak menjalar di payudaraku.
Setelah selesai mengurus administrasi, suamiku membantuku menggendong Jadu dan mengangkat sebagian barang-barang ke mobil. Aku rasanya ingin memeluk dia hari ini, namun tagihan rumah sakit rupanya membuat ia tak kuasa menangkap getar-getar rasa rindu yang aku tebar. Kembali hening, sepanjang perjalanan aku, Jadu dan ayahnya hanya diam.
Sesampainya dirumah aku disambut riang Jatu yang baru pulang dari sekolah. “Bundaaaa…..” Teriaknya, “Kakaaaaak…” Aku turun dari mobil sambil menggendong dari mobil sambil menggendong Jadu. “Adiik, sudah sembuh kan ?” Tanya Jatu sambil membelai Jadu adiknya. Aku tersenyum melihat adegan itu. MasyaAllah, nikmat yang lupa aku syukuri bahwa aku memiliki 3 anak laki-laki yang saling menyayangi meski tak bisa dipungkiri ada perang-perangan di dalamnya.
“Aku langsung ke kantor ya sayang,” Masih di dalam mobil suamiku berkata. Aku menatapnya heran, “Kamu tuh kerja atau menghindar dari aku sih ?” Kalimat pemancing keributan yang gak bisa aku tahan keluar tanpa sadar dari mulutku. “Apa ?” Ia bukan tak mendengar, ia meminta aku untuk mengulanginya untuk memastikan bahwa aku benar-benar mempertanyakannya. Ia keluar dari mobil lalu mengejarku yg hendak ke kamar untuk memindahkan Jadu dari gendonganku. “Sayang, aku mau bicara.” Katanya.
“Bukannya mau buru-buru ke kantor ?” Argh, aku menyesal lagi-lagi menjadi istri yang tak peka. Pertanyaanku kali ini memberhentikan langkahnya, ia menghela nafas dan berbalik. “Iya, aku berangkat.”
Dan aku melihatnya dengan mata nanar. Ada dua sisi hati yang bertengkar, satu memarahi diriku yang salah mengambil tindakan. Satu memarahi dia yang tak cukup peka dengan kondisi istrinya. Komunikasi yang buruk untuk pasangan suami istri yang hampir 8 tahun menikah.
“Bun, si Jati demam.” Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara dibelakangku yang terdengar setengah panik. Mba ART yg baru 2 bulan bekerja di rumah tampak menggendong putra bungsuku sambil memberikannya dot ASI. “Ya Allah Ya Rabbana, kenapa lagi ini ?” tanyaku. “Jati dari kemarin pup terus bu.” Jawabnya sambil menyodorkan Jati ke tanganku. Buyar sudah harapan untuk bisa rebahan di tempat tidur yang nyaman. Bungsuku tampak pucat, dan aku kembali melihat tanda dehidrasi yang dialami Jadu 3 hari lalu ada di Jati hari ini. “Kenapa gak ngabarin dari kemarin sih ?” Aku setengah berteriak. Kesal bukan main, segera aku pencet nomor suamiku yang baru saja meluncur mobilnya keluar gerbang.
“Kita balik ke rumah sakit, sekarang giliran Jati yang sakit.”
Di dalam mobil aku menangis sejadi-jadinya sambil menggendong Jati. Perasaan lelah, 20 ribu kata yang gak keluar beberapa hari, tangki cinta yang kosong, dan segala tumpukan rasa jengah hanya bisa meluncur lewat isakan tangis. Suamiku diam, seperti biasa. Mungkin dia juga bingung harus bagaimana, rentetan peristiwa pekan ini tak hanya membuat aku jengah, tapi juga membuat ia jadi tak keruan.
“Maafin aku sayang.” Selepas aku menahan diri untuk berhenti menangis, dia lirih berbisik. “Semua karna aku.” Katanya. Aku menggeleng, “Nggak.. aku yang salah karna aku gak becus jagain anak-anak.”
“Aku nggak kasih kesempatan kamu untuk jadi ibunya anak-anak.” Ia berkata pelan, “Plis.. aku minta kamu pulang ya. Jagain anak-anak aku. Kita urus resignnya kamu setelah ini.” Aku menatapnya penuh haru. Beberapa tahun terakhir ini kami memang sering bersitegang karena masalah ini. Apalagi setelah si Jati lahir, keinginanku untuk resign semakin kuat meski aku seorang pegawai negeri sipil yang kebanyakan orang sangat ingin menduduki posisiku saat ini. Namun drama ART, keseharian yang dekat komunitas parenting dan pekerjaan yang nggak sesuai passion membuat aku ingin segera pulang, kembali menjalankan peran yang Allah beri yakni sebagai istri dan ibu. Tapi sebagai seorang suami aku paham betul bahwa dia perlu menganalisa, memperhitungkan dan memastikan bahwa jalan yang akan kami tempuh ini benar sehingga proses acc dari beliau tentu tidak main-main.
“Bun, kalo kamu resign nanti aku mungkin hanya akan mampu memenuhi kebutuhan hidup kita sekeluarga. Untuk gaya hidup, kamu cari sendiri ya.” Jleb! Aku tersenyum dibalik kalimat suamiku yang penuh makna. Bisa jadi itu adalah nasihat jangan boros, karena hobi ku salah satunya adalah jajan. Atau bisa jadi itu adalah lampu hijau yang mengizinkan istrinya untuk tetap produktif meski dirumah aja.
***

Setahun berlalu setelah proses panjang dari resign-ku di salah satu lembaga pemerintahan. Alhamdulillah kini aku telah sampai di rumah, menikmati kebersamaan dengan anak-anakku, menjadi ibu yang seutuhnya buta mereka.
Banyak yang bilang bahwa aku telah berkorban untuk suami dan anak-anakku karena rela melepas karir dan statusku sebagai Aparatur Sipil Negara, padahal aku hanya pulang untuk menghentikan pengorbanan anak-anakku yang menunggu sekian lama karena ibunya asyik bekerja.
“Assalamualaikum.”
“Abi pulang!” Teriak anak-anak menyambut ayahnya datang. Aku berlari ke arah pintu ikut antri menyambut dia yang lelah seharian di tempat kerja. Memeluknya dengan hangat, dan berbisik mengatakan terima kasih sudah berjuang untuk kami dan keluarga. Ia tersenyum lalu berkata, “Terima kasih juga sayang, sudah mau menjaga anak-anak dan mengurus rumah. Abi nggak bisa bales semua ini, selain Allah yang akan membalasnya dengan pahala berlipat ganda,”
MasyaAllah Tabarakallah. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan aku dustakan ?